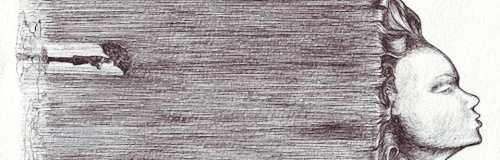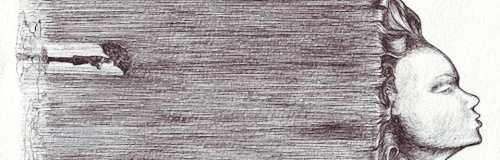
PRAAAANGGG!
Piring di dapur pecah satu-satu. Andita melemparkannya sebagai bentuk amarah yang seringkali tak terkendali. Perempuan itu menangis, sementara tangannya sibuk meraih piring, gelas lalu melemparkannya ke mana saja. Ke lantai, ke tembok. Meretakkan sunyi yang terjadi berjam-jam lalu.
“Andita, hentikan!” aku menarik tubuhnya menjauh dari rak piring. Tangannya meronta. Perempuan itu terus saja menangis.
“Brengsek kamu, mas! Kamu selingkuh kan? Iya kan?” PRAAANGGG! satu piring dibanting lagi ke depan wajahku. Air matanya leleh serupa lilin yang dibakar api. Bahunya terguncang sebab tangisannya yang memilukan.
Kegusaranku semakin menjadi, kutarik tangannya, tak peduli perempuan itu akan meronta atau mencakar lenganku. Andita sudah kelewatan! Beling-beling gelas dan piring yang berserakan di lantai, kulewati begitu saja tanpa peduli goresannya akan melukaiku dan kaki Andita. Dia sudah kelewatan membuatku muak!
“Mas,lepas, Mas! Brensek kamu, mas! Bajingan!” makinya terus-terusan. Kalau aku bisa tega, mungkin aku bisa menamparnya karena ucapannya yang tak pantas. Tapi aku tak sampai hati melakukannya.
“DIAM! Kamu sudah kelewatan, Dita!” aku mencengkram tangannya. Dita masih menangis sesegukan. Berteriak kesakitan, aku tidak peduli lagi.
“Sakit, mas, lepas!” perempuan itu terus meronta di depanku.
Setelah keluar dari dapur, aku melepasnya.
“Kenapa kamu melakukan itu semua?” tanyaku gusar. Mataku menatapnya tajam, sementara dia masih sibuk menangis.
“Harusnya aku yang bertanya begitu sama kamu, mas!” suara Dita meninggi. Tatapannya tak kalah tajam.
“Apa? Apa yang mau kautanyakan? Apa lagi yang mau kautuduhkan?”
Dita terdiam. Wajahnya membuang muka. Masih menangis.
“Kamu selingkuh! Iya kan?” suara Dita makin meninggi. Perempuan itu sekarang sudah berani mengarahkan telunjuknya ke wajahku.
“Bukti dari mana? Kamu jangan asal menuduh ya?!” Aku semakin gusar. Pertengkaran itu tak lagi dapat terelakan lagi. Andita sudah keterlaluan. Semakin hari, semakin muak saja aku padanya. Perangainya dari dulu tak berubah, sikap cemburunya pun sama.
Dengan gontai langkah Dita menuju kamar, lalu kembali lagi bersama buntalan kemeja putih yang kemarin malam kukenakan.
“Ini apa, mas? APAAA?” Dia melemparkan kemeja itu ke depan wajahku. Pada bagian kerah, aku melihat noda merah muda itu. Noda lipstickperempuan.
“Cium, kemeja itu, mas. CIUM!!” kini Andita menjejalkan kemeja itu ke hidungku. Sekilas, terhirup bau yang asing. Wangi parfum perempuan.
Aku menelan ludah. Habislah sudah, riwayatku.
Perempuan di depanku kini tengah sibuk melepas dasi di kemejaku. Dengan senyum yang terlampir di wajahnya, dia mampu menghapus segala lelah juga kerumitan-kerumitan yang sedang kualami. Aku mengecup keningnya. Debar ini masih utuh untuknya. Belum pernah berkurang sedikit pun. Perempuan itu tertawa.
“Aku rindu kamu, mas.” katanya masih dengan melepas dasi lalu disusul membuka kancing kemejaku.
Kukecup kening itu untuk kedua kali. “Aku juga.” kataku sambil tersenyum. Sudah hampir satu minggu kami tak bertemu lagi. Kesibukan di kantorku, dan urusan yang kian meruncing di rumah, membuatku jarang menemuinya. Dia tersenyum samar. Rambutnya yang lurus dan kemerah-merahan nampak makin menggodaku di kala malam seperti ini. Perempuan itu kini dibalut kemeja putih yang kebesaran di tubuhnya, saking kebesarannya, celana pendeknya pun tertutupi dengan itu. Aku selalu suka bila dia menyambutku dengan penampilannya yang seperti itu; membuatku merasa semakin tertantang untuk mencintainya.
Kancing itu hampir habis ia lepaskan. Lalu dia memajukan tubuhnya untuk melepas kemejaku. Sekilas, tercium aroma tubuh yang bercampur parfum yang sering ia kenakan; aroma yang sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Aroma yang sampai kini terus kuingat; cinnamon. Aroma yang tak pernah gagal menghangatkan tubuh dan ingatanku.
Beberapa menit kemudian, tubuhku dan tubuhnya sudah saling berhadap-hadapan. Siap untuk saling mencintai dari posisi yang berlawanan. Atas-bawah. Kuturunkan bibirku sedikit untuk mencium bibirnya yang lembut. Bibir yang dulu hanya membayangiku lewat mimpi. Bibir yang pernah kuterka seberapa lembut rasanya. Kini aku merasakannya. Tekstur bibirnya, tarikan bibir yang saling berpagut, harum liurnya, dan seberapa manis ludah yang saling kita tukar.
Malam ini angin tak mampu lagi mengeringkan tubuh kita yang saling basah. Dinginnya udara malam tak dapat lagi menyentuh kita yang sedang membara dalam lenguhan yang panjang. Suara burung hantu ataupun jangkrik tak terdengar, lenyap oleh suara rintihan dan bunyi-bunyian yang lain. Kita sepasang dosa yang sedang melawan arus takdir yang begitu kejam. Kita sepasan do’a yang tak pernah terkabul, lalu berontak dengan dosa-dosa yang sedang kita perbuat.
Satu tarikan napas terdengar lebih mirip seperti lenguhan.
“Aku….hh…mencintaimu…” bisiknya lembut.
“Aku..juga….hh..” balasku. Kucium lagi bibirnya. Untuk kali terakhir di malam ini. Aku, sungguh-sungguh mencintaimu, lanjutku dalam hati.
Andita sudah menungguku di depan pintu ketika aku baru saja masuk ke dalam rumah. Wajahnya tersenyum. Berbinar-binar. Ini kejadian langka. Biasanya, dia selalu memamerkan wajah muak, kesal, bosan, marah ketika aku sampai di rumah. Tapi ini berbeda. Wajahnya tersenyum. Bibirnya menyungging senyum paling lebar. Dan aku, pernah jatuh cinta dengan senyumnya yang seperti ini.
Berbeda dengan malam satu minggu sebelumnya, ketika dia heboh membanting hampir seluruh perkakas makan di dapur, malam ini Andita terlihat cantik sekali dengan senyum menawan yang pernah memikat hatiku dulu. Akhirnya, selama berbulan-bulan, aku menemukan oase di tengah gurun pasir. Aku menemukan sedikit harapan atas kacaunya rumah tanggaku belakangan ini.
“Mas…sudah pulang? Aku menunggu kamu dari tadi, lho..” katanya lembut sambil melepas dasi dan kemejaku. Seingatku, ini kali pertamanya dia lakukan sejak pernikahanku satu tahu lalu.
“Ngg…kamu kok tumben, bun manis begini…” kataku menggodanya. Dia tersenyum, matanya menyimpan banyak rona bahagia.
“Aku cuma mau jadi istri yang baik buat kamu, mas.” katanya lembut. Lalu tubuhnya memelukku. Seperti ada yang salah, dia memelukku lama sekali. Seakan takut kehilangan aku.
“Mas, aku hamil.” ujarnya senang.
Seperti tersengat ribuan lebah, aku terpaku. Terkejut dengan kalimat yang baru saja diucapkan perempuan yang sedang memelukku ini. Andita hamil. Ini jelas kabar baik buat keluarga kecilku. Segelintir rasa gembira ikut hadir dalam benakku. Andita hamil. Artinya, sebentar lagi aku akan menjadi Ayah seutuhnya untuk calon bayi mungil yang belum bernama itu.
Namun segelintir rasa cemas juga turut hadir di pesta kecil itu.
Ingatan tentang seorang perempuan.
Riana. Perempuan berambut lurus kemerah-merahan. Perempuan yang gemar mengenakan kemeja longgar tiap kali aku datang. Perempuan yang selalu menungguku dalam flat nomor 56 di apartemen bergengsi di bilangan Jakarta. Perempuan yang selalu menungguku sejak dulu. Perempuan yang aku cintai. Sejak dulu. Jauh sebelum Andita hadir di hidupku. Perempuan beraroma cinnamon.
Malam, pukul sebelas waktu Indonesia bagian barat.
Hujan mengguyur Desember setiap malam. Hujan yang selalu dijadikan alas kaki untuk terhindar dari beling-beling. Hujan yang kerap dijadikan alasan demi dosa-dosa yang indah dan direncanakan.
Basah kuyup, tanpa payung, aku berlari menuju gedung apartemen Riana dari tempat parkir mobil. Derap langkahku bergetar, memasuki kotak bernamakan lift dan menekan nomor lantai tempat di mana Riana menungguku.
Setiap bunyi lift, tanda satu-satu lantai telah dilewati ialah bunyi lain dari kecemasan yag satu-satu ikut membuncah di dadaku. Kita semakin dekat dengan kesedihan, bisikku dalam hati.
Tokk..tokk..tok..
Kuketuk pintu flatnya tergesa-gesa. Tak ada jawaban. Kuketuk lagi untuk kedua kali. Tak lama pintu terbuka.
Perempuan berdiri dengan mata bundarnya yang kelihatan terkejut, sebab aku tak mengatakan akan datang. Kemudian dia tersenyum lebar, sambil bibirnya rewel karena tak bilang akan datang dan karena tubuhku yang kini kuyup kebasahan.
“Kamu kok nggak bilang mau ke sini. Mau bikin kejutan ya? Kebiasaan kamu mah bikin aku terkejut terus. Aduh…baju kamu basah banget. Aku ambilin bajumu di lemariku, ya?” katanya rewel. Aku hanya menatap punggungnya yang makin berlalu menuju kamar, megambil sepotong bajuku yang ia simpan di lemarinya. Untuk mengobati rindu, katanya.
“Tidak usah, Ri. Aku hanya sebentar.” kataku menghentikan langkahnya. Dia menoleh.
“Lho, sebentar? Ada apa, mas?” tanyanya sambil kembali menghampiriku. Aku menarik napas panjang. Rasanya berat sekaligus sesak.
“Ri…aku bingung memulainya dari mana..” aku tak berani menatapnya yang duduk di sampingku dengan wajah bertanya.
“Ada apa, mas? Kabar buruk?” tanyanya menebak. Tangannya kini sibuk mengusap punggungku. Mencoba menenangkanku. Percuma, semakin ia membelaiku, semakin sedih aku mengatakan ini padanya.
Aku mengangguk. Sebagai jawaban, ya ini kabar buruk. Sekaligus gembira di lain sisi.
“Istriku hamil, Ri…” desahku pelan setelah jeda yang lumayan panjang. Hening. Tak ada yang keluar baik dari bibirku maupun bibir lembut Riana.
“Bukankah itu kabar baik?” tanyanya. Aku menoleh. Memberanikan diri menatap wajanya yang sedang tersenyum. Walau aku tahu di sana terselip kesedihan yang sangat kentara.
“Di satu sisi, memang kabar baik. Tapi, Ri..” aku tak sanggup melanjutkan kata-kataku. Hening lagi. Kata-kataku menggantung bagai do’a yang tak pernah terjawab.
“Aku tak bisa meneruskan ini..” kataku akhirnya. Ucapan selamat tinggal yang buruk.
Riana melepas tangannya dari punggungku. Kemudian dia sibuk memandangi jari-jemarinya sendiri di pangkuan.
“Aku sudah tahu ini akan terjadi pada kita, mas..” ujarnya pelan. Kepalanya terus menunduk. Menahan tangis yang tak ingin ia tumpahkan, kurasa.
“Takdir memang tidak pernah menginginkan kita.” lanjutnya sedih. Aku masih menatapnya yang kini tenggelam dalam lamunan dan lipatan buku-buku di jarinya.
“Aku mencintaimu, Ri…” aku mengatakan lagi kalimat serupa berulang kali padanya.
“Aku tahu.” balasnya singkat. Masih menundukan kepala.
“Tetapi itu cukup. Aku tidak ingin mencintaimu lebih jauh lagi. Aku tidak ingin melukai kita semakin dalam.”
“Aku paham…” balasnya. Kali ini dengan suara tangis yang samar terdengar.
“Ri….” aku memanggilnya. Kita sama-sama hening dalam ramai di kepala kita masing-masing. Saling mengumpat, mengapa takdir harus setega ini memisahkan dua hati yang tak pernah bisa menyatu. Mengapa takdir harus membiarkan dua hati saling terluka dengan cintanya. Cinta yang katanya agung. Cinta yang katanya bisa membahagiakan hidup seseorang. Namun yang kurasakan, justru sebaliknya.
“Lepaskanlah aku selagi sanggup, mas. Sebelum cinta membuatmu lupa jalan pulang.” gumamnya pelan.
“Aku bukan rumah yang disediakan takdir untukmu, pulanglah. Lepaskanlah aku. Kita memang seharusnya tidak memulai ini.” lanjutnya lagi. Kudengar, tangisnya semakin kentara. Jelas. Bunyi kesedihan yang paling menyayat. Kutarik tubuhnya dalam dekapanku. Perempuan itu tak meronta sama sekali. Dia pasrah jatuh pada dadaku yang selalu lapang untuknya. Untuk tangisannya yang semakin pecah di hening malam ini. Suaranya serupa suara pecahan beling yang Andita lemparkan ke lantai ataupun ke tembok. Bunyi lain dari kesedihan dan amarah paling dalam.

Malam ini, tak ada lenguhan panjang, tak ada hasrat liar yang bergemuruh dalam dada, tak ada basah yang menyenangkan kecuali air mata kesedihan Riana di kemejaku. Malam ini, angin malam mampu menggigilkan kita yang berpeluk tanpa berpeluh, udara malam mampu membekukan hangat bara api yang dulu singgah di dadaku ketika kita berdua dalam satu ruang, dan suara burung hantu juga jangkrik terdengar lebih lantang dari biasanya. Malam ini, aku menghirup lagi aroma cinnamon lebih panjang, lebih dalam lagi, untuk diingat dalam jangka waktu yang lama. Sekali lagi.
Tak mungkin menyalahkan waktu
Tak mungkin menyalahkan keadaan
Kau datang di saat ku membutuhkanmu
Dari masalah hidupku bersamanya
Semakin ku menyayangimu
Semakin ku harus melepasmu dari hidupku
Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini
Kita tak mungkin terus bersama
Suatu saat nanti kau kan dapatkan
Seorang yang kan damping hidupmu
Biarkan ini menjadi kenangan
Dua hati yang tak pernah menyatu
Maafkan aku
Yang membiarkanmu masuk ke dalam hidupku ini
Maafkan aku
Yang harus melepasmu walau ku tak ingin
Semakin terasa cintamu
Semakin ku harus melepasmu dari hidupku
I will let you go
I will let you go
I will let you go…